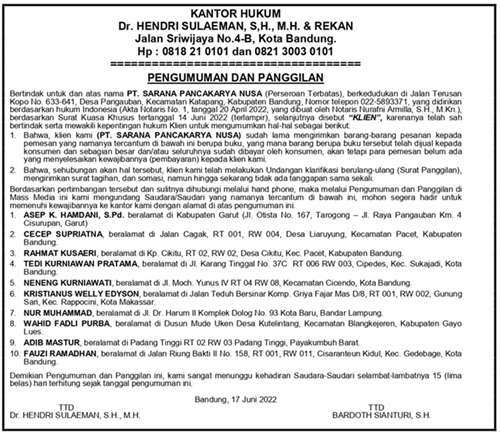Penulis: Kaka Suminta
13 Jam lalu, Dibaca : 64 kali

Oleh Kaka Suminta
International
Observer
Perjalanan
Panjang Jakarta-Dhaka dengan transit di Kuala Lumpur yang memakan 8 jam di
perjalanan menjadi terasa ringan ketika saya menyaksikan perubahan signifikan
struktur politik Bangladesh, yakni berakhirnya dominasi kekuasaan Liga Awami di
bawah kepemimpinan Sheikh Hasina. Pemilu ini menjadi rangkaian perubahan
politik Bangladesh abad ke-21. Setelah sebelumnya terjadi apa yang disebut
Revolusi Juli 2024, yakni ketika mahasiswa dan masyarakat mampu menumbangkan
rezim represif tadi. Bisa dikatakan perubahan besar ini merupakan revolusi
pertama Gen Z di Asia, bahkan di dunia, yang berhasil mengubah keadaan.
Perjalanan
selanjutnya saya terbang ke Division (setingkat Provinsi) Rajshahi di barat
laut Dhaka yang ditempuh pesawat jenis ATR selama sekitar 45 menit. Organisasi
pemantau pemilu Asia, Asian Network for Free Election (ANFREL) yang bermarkas
di Bangkok menempatkan saya di division ini, yang merupakan salah satu dari 8
division di seluruh Bangladesh. Maka pemantauan pemilu dan upaya untuk
memberikan makna revolusi Gen Z tadi dimulai sepekan sebelum pemungutan suara
12 Februari 2026 atau lebih dari setahun setengah setelah Revolusi Juli 2024.
Rajshahi
menyambut saya dengan udara yang lebih sejuk dari Dhaka, meski matahari
Februari tetap membakar ubun-ubun. Kota yang dikenal sebagai kota sutra ini
tengah bersolek. Spanduk-spanduk biru langit bergambar tanda tangan—simbol
Komisi Pemilihan Umum Bangladesh yang baru—terpampang di hampir setiap sudut
jalan. Namun yang lebih menarik perhatian bukanlah atribut kampanye, melainkan
wajah-wajah muda yang duduk di depan balai desa, sekolah, bahkan di bawah pohon
beringin, tengah asyik mendebatkan program calon anggota parlemen setempat.
Di sinilah
revolusi Gen Z menemukan wujud konkretnya. Bukan lagi sekadar narasi heroik di
media sosial tentang gugurnya pahlawan muda di persimpangan jalan Dhaka, tetapi
sebuah kesadaran politik baru yang menolak untuk kembali ke masa lalu. Selama
seminggu berkeliling Rajshahi, saya bertemu dengan setidaknya tujuh pemuda yang
pernah menjadi koordinator lapangan saat Revolusi Juli. Mereka kini menjadi
relawan pemilu, pelatih saksi, bahkan calon anggota dewan kota. Nama-nama
seperti Rohan, Nafisa, dan Shamsul mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah
resmi, tetapi mereka adalah arsitek perubahan yang sesungguhnya.
"Saya
belajar dua hal dari revolusi," ujar Rohan, mahasiswa tahun ketiga jurusan
Sastra Inggris yang kini tercatat sebagai koordinator pemuda untuk salah satu
kandidat independen. "Pertama, bahwa pemerintah bisa jatuh jika rakyat
bersatu. Kedua, bahwa menjatuhkan pemerintah jauh lebih mudah daripada
membangun tata kelola yang baru." Ia tersenyum getir. Senyum yang sama
saya lihat di wajah aktivis reformasi di Indonesia tahun 1998, atau di Kairo
tahun 2011. Ada kebanggaan, tetapi juga kesadaran akan beban yang kini
dipanggul.
Asia
Network for Free Election menugaskan tim kami untuk memantau enam distrik di
Rajshahi. Dalam setiap kunjungan ke tempat pemungutan suara (TPS), kami
menggunakan formulir standar yang mencakup 42 indikator, mulai dari
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas hingga potensi intimidasi. Namun,
catatan saya lebih banyak terisi oleh pengamatan sosiologis ketimbang sekadar
daftar periksa teknis.
Di sebuah
desa bernama Puthia, yang terkenal dengan kompleks kuil kunonya, saya
menyaksikan simulasi pemungutan suara yang difasilitasi oleh sekelompok
mahasiswa. Mereka telah merancang aplikasi sederhana berbasis Android untuk
melacak dugaan kecurangan real-time. Tiga tahun lalu, aplikasi serupa mungkin
akan berujung pada penangkapan oleh pasukan keamanan. Hari ini, perangkat lunak
itu diuji coba di hadapan pejabat komisi pemilu setempat. Generasi yang tumbuh
bersama koneksi internet 4G ini tidak hanya piawai dalam aksi jalanan, tetapi
juga dalam merancang infrastruktur demokrasi digital.
Namun,
revolusi tidak pernah berjalan lurus. Pada hari ketiga pemantauan, saya
menerima laporan dari tim di distrik tetangga, Chapai Nawabganj. Sekelompok
preman bayaran mencoba merusak logistik pemilu di sebuah gudang kecamatan. Yang
menarik bukanlah insidennya—karena hampir semua pemilu di Asia Selatan memiliki
cerita serupa—melainkan respons warganet. Dalam hitungan jam, video amatir
tentang percobaan perusakan itu tersebar di TikTok dan Instagram. Algoritma
media sosial, yang dulu digunakan rezim Liga Awami untuk membungkam kritik
melalui UU Kekuasaan Digital, kini menjadi alat akuntabilitas publik.
Apakah Gen
Z Bangladesh sadar bahwa mereka sedang menciptakan preseden global? Sejauh
pengamatan saya, hanya segelintir yang menyadarinya. Kebanyakan dari mereka
terlalu sibuk dengan urusan teknis: memastikan tinta tidak mudah luntur,
mengawasi proses sortir surat suara, atau membantu para lansia menemukan nama
mereka dalam daftar pemilih. Revolusi, bagi mereka, adalah soal memindahkan
kursi plastik ke tempat teduh agar para ibu hamil tidak kepanasan saat
mengantre. Revolusi adalah soal menolak menerima amplop cokelat berisi uang
dari calon legislatif. Revolusi adalah rutinitas baru yang melelahkan tetapi
membanggakan.
Sore hari
menjelang pemungutan suara, saya berbincang dengan seorang petugas KPPS bernama
Farida Begum. Ia berusia 52 tahun dan telah menjadi guru madrasah selama tiga
dekade. "Saya tidak mengerti politik," katanya dalam bahasa Bengali
yang pelan. "Tapi saya tahu anak-anak saya yang lulus universitas kini
punya pekerjaan. Bukan karena rezim baru memberi mereka jabatan, tetapi karena
mereka tidak takut lagi untuk membuka usaha sendiri. Mereka tidak perlu menyuap
pejabat untuk mengurus izin." Farida tidak menyebut kata
"revolusi", tidak pula "Gen Z". Ia hanya bercerita tentang
anak bungsunya yang kini membuka kafe kecil di dekat stasiun kereta.
Malam 11
Februari 2026 menjadi malam paling sunyi di Rajshahi sejak kedatangan saya.
Toko-toko tutup lebih awal. Jalanan nyaris sepi. Tim pemantau berkumpul di
ruang tamu sewaan, menyusun strategi distribusi ke 47 TPS yang tersebar di
wilayah rawan. Generasi milenial dan Gen Z tidur lebih awal malam itu, bukan
karena lelah, tetapi karena mereka paham bahwa esok adalah pertaruhan terbesar
dalam hidup mereka.
Pukul 5.45
pagi, saya tiba di TPS 03 Kelurahan Motihar. Antrean telah mengular sejak pukul
5. Seorang perempuan muda berjilbab oranye berdiri paling depan. Ia membawa map
plastik berisi dokumen kependudukan yang dilaminating agar tidak lecek. Saya
bertanya, sudah berapa lama ia menunggu. "Sejak subuh. Saya tidak mau
terlambat. Saya tidak mau golput seperti ibu saya dulu." Namanya Sumaiya,
22 tahun, mahasiswi semester akhir jurusan Teknik Sipil Universitas Rajshahi.
Hari
pemungutan suara berjalan dengan kecepatan yang aneh. Kadang terasa lambat
ketika kami harus menunggu berjam-jam di posko koordinasi, kadang terasa cepat
ketika laporan dari berbagai distrik mengalir deras. Tidak ada insiden besar
yang dilaporkan. Seorang saksi dari partai kecil mengeluh karena saksi dari
partai besar duduk terlalu dekat dengan kotak suara. Di TPS lain, seorang
lansia menangis karena sidik jarinya gagal terdeteksi oleh alat verifikasi
biometrik. Masalah-masalah kecil yang justru menandakan bahwa demokrasi sedang
bekerja.
Ketika
matahari terbenam dan penghitungan suara dimulai, saya menyadari sesuatu yang
mungkin luput dari banyak analis politik. Revolusi Gen Z di Bangladesh tidak
terutama tentang usia, teknologi, atau bahkan media sosial. Revolusi ini adalah
tentang keberanian untuk membayangkan bahwa hal-hal biasa—seperti antre untuk
memilih, seperti protes yang tidak berujung pembunuhan, seperti laporan
keuangan kampanye yang bisa diakses publik—adalah sesuatu yang layak
diperjuangkan sampai mati. Dan mereka yang bertahan hidup kini bertugas merawat
kewajaran itu agar tidak direbut kembali oleh kekuatan lama.
Saya
meninggalkan Rajshahi dua hari setelah Komisi Pemilihan mengumumkan hasil
sementara. Partisipasi pemilih mencapai 78 persen, tertinggi dalam dua dekade
terakhir. Di ruang tunggu bandara, saya membuka kembali buku catatan. Halaman
terakhir hanya berisi satu kalimat yang saya tulis sambil lalu: "Bagaimana
mengukur keberhasilan revolusi?" Mungkin jawabannya tidak perlu dicari di
Dhaka, di parlemen, atau di istana presiden. Mungkin jawabannya ada di
Rajshahi, di TPS 03, pada seorang perempuan muda yang bangun sebelum subuh
hanya untuk menggunakan hak pilihnya. Mungkin revolusi berhasil justru ketika
ia tidak lagi disebut sebagai revolusi, melainkan telah menjadi keseharian yang
lumrah.
Pesawat ATR
itu kembali membawa saya menembus awan tipis di atas Sungai Padma. Di bawah,
sawah-sawah menghijau dan permukiman padat bergantian menghilang di balik
gumpalan putih. Delapan jam transit di Kuala Lumpur masih menanti sebelum
penerbangan lanjutan ke Jakarta. Namun, kali ini perjalanan pulang terasa lebih
ringan dari perjalanan datang. Bukan karena saya terbiasa, tetapi karena saya
membawa pulang sesuatu yang dulu sempat saya ragukan: keyakinan bahwa generasi
muda, ketika diberi ruang dan kepercayaan, mampu menulis ulang takdir bangsanya
sendiri.
Terpikir
oleh saya, apakah di sudut lain Asia Tenggara, di negeri saya sendiri, sedang
lahir gerakan serupa yang kelak juga akan mengubah segalanya. Revolusi bukan
monopoli satu generasi. Mungkin ia hanya menunggu waktu untuk mengetuk pintu revolusi
perubahan lagi. Sebuah revolusi Gen Z di negeri sendiri.
 Penghitungan suara di Bangladesh
Penghitungan suara di Bangladesh
Tag : No Tag
Berita Terkait
Rehat
Tajuk

Memahami Pemikiran Jenderal Dudung Abdurachman

PERLUNYA MENGUBAH CARA PANDANG PEDAGANG DI LOKASI WISAT...

Berita Populer
Arief Putra Musisi Anyar Indonesia
Ketua Umum GRIB H Hercules Rozario Marshal, Saya Bagian Dari Masyarakat Indramayu
Project Fly High Terinspirasi dari Pengalaman Hidup Dr Joe dan Tamak
Dari Kegiatan Aksi Sosial, Hercules Kukuhkan Ketua DPC GRIB JAYA Se-Jawa Barat
Chief Mate Syaiful Rohmaan
SAU7ANA
GMBI Kawal Kasus Dugaan Penipuan PT. Rifan Financindo Berjangka di PN Bandung
Indramayu Diguncang Gempa Magnitudo 4.4, Kedalaman 280 Kilometer
Ivan Lahardika Arranger dan Komposer Indonesia
SAU7ANA Come Back